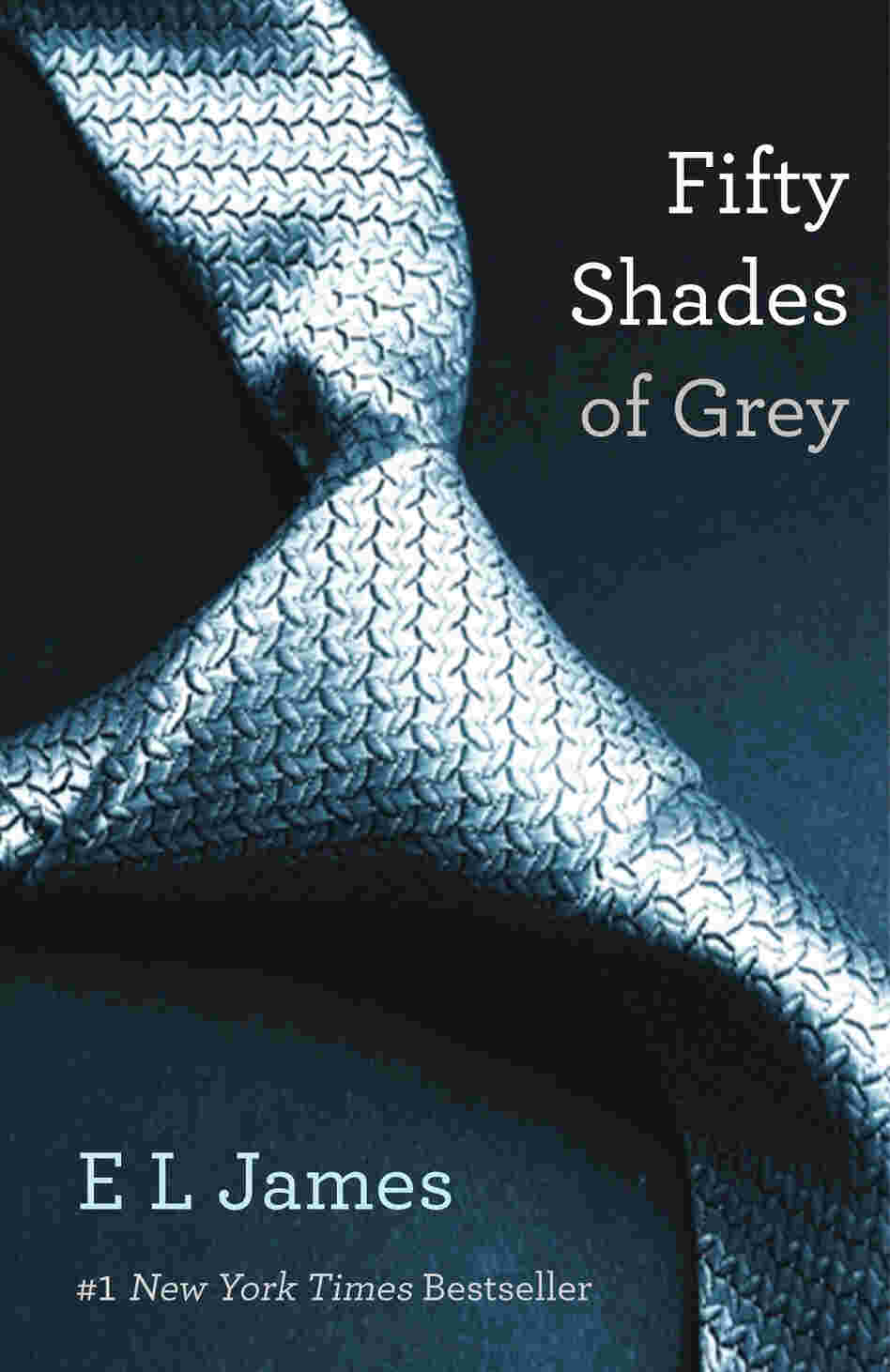Sembari menciduk air untuk membersihkan
sayur dan umbi, aku bertanya-tanya kenapa aku harus memasak. Untuk memenuhi
tuntutan masyarakat? Supaya suamiku kelak tidak menyesal? Sepertinya karena
sudah buntu dengan menulis.
Nyonya Teladan lagi tidak ada. Setelah
lama tidak masak, kali ini aku merasa bagai kali pertama. Aku harus mulai dari
yang sederhana.
Belakang aku terbayang-bayang bayam.
Tidak kusangka akan kutemukan di kulkas. Googling
dengan kata kunci “bening bayam”.
Papa merebus potongan daging ayam.
Kutanya buat apa. Sebagian untuk sop, sebagian untuk digoreng. Ketimbang diolah
tanpa kreativitas, aku putuskan sebagian untuk sambal goreng. Googling dengan kata kunci “sambal
goreng” sekalian.
Untuk
sambal goreng, kurang kentang,
daun salam, serai, lengkuas, cabai rawit, gula merah, asam jawa, cabai
keriting, merica, terasi…
Tidak masalah. Bening bayam bisa tanpa
jagung dan temu kunci. Sambal goreng, minimal cabai keriting. Bukan pertama
kali aku bikin bening bayam dan sambal goreng. Pada pengalaman-pengalaman
sebelumnya pun aku tidak selalu patuh pada resep alias jalan dengan bahan
seadanya.
Bening
bayam
Mestinya ini bayam dari Carrefour. Walau
jarang mengolah sayur, aku tahu macam apa bayam yang buruk. Barangkali karena
bayam ini sudah beberapa hari di kulkas—aku tidak ingat kapan terakhir Papa
belanja.
Aku petiki jua helai demi helai dua ikat
bayam itu, jumlah yang pas dengan resep. Kukuliti bawang merah. Kuambil wortel
seperlunya, tanpa timbang-timbang, kupotong ujung-ujungnya, kubersihkan
permukaannya. Bersama sebutir tomat, kucuci mereka tiga kali.
Bawang merah kuiris-iris. Resep bilang
wortel dipotong miring, aku lupa, biarlah. Aku belah tomat beberapa bagian,
untung tidak hancur.
Aku takar air 250 ml, kutuang ke panci.
Terlalu sedikit…! Aku tengok resep, ternyata 2.500 ml, ganti panci. Aku biarkan
panci berisi air itu pada kompor menyala hingga muncul gelembung-gelembung kecil.
Aku tidak sabar untuk memasukan potongan-potongan bawang…
Kupandangi potongan-potongan kecil tak
keruan itu, semula terpuruk di dasar lantas terangkat perlahan-lahan ke
permukaan. Menari-nari digerakkan gelegak air. Rebus sampai harum, kata resep.
Haruskah kucium? Barangkali temu kunci yang bikin harum, aku lebih ingin temu
kangen… Air semakin mendidih. Berikutnya lingkaran-lingkaran oranye yang
berterbangan di ceruk panci.
Masak sampai empuk, kata resep. Beberapa
lama. Kuambil satu potongan dengan pisau. Kubelah di talenan. Kuicip
panas-panas. Masih keras. Kuamati lagi potongan-potongan wortel yang
berloncatan beberapa lama. Kuambil lagi sepotong. Kubelah. Kuicip. Rasa wortelnya
masih kentara. Sekali lagi. Belum. Kutinggal deh. Berikutnya wortel sudah
sangat empuk.
Sesuai resep aku cemplungkan satu sendok
teh gula, aku suka manis, aku lebihkan, satu lagi, lalu, semoga resep ini tidak
salah, 5 ½ sendok teh garam, sepertinya kebanyakan, jadi tidak pakai ½, aku
tambahkan lagi gula, terakhir potongan tomat.
Warna-warni berdansa-dansi di kawah
panci. Masak sampai mendidih, kata resep. Sudah mendidih dari tadi, batinku.
Kumasukkan helai-helai bayam. Masak sampai matang, kata resep. Memang aku tahu
bayam yang matang seperti apa? Wortel sudah sangat empuk tadi. Aku bolak-balik
isi panci dengan pisau, sampai kira-kira dedaunan itu cukup lemas.
Aku cicipi sedikit kuah bening yang
tidak begitu bening itu. Sepertinya keasinan. Mungkin aku memang sudah ingin
kawin...
Sambal
goreng
Di warung hanya tersedia cabai keriting,
merica bubuk, dan terasi. Ada cabai merah besar, tapi melihat mereka aku tidak
selera. Harus pilah-pilih lagi. Sudah siang saat itu, masak sempat ditunda
karena ada urusan di luar rumah yang bikin buruk suasana hatiku. Aku singgah
sebentar di Alfamart untuk beli es krim Sponge Bob, tidak dicantumkan dalam
resep, aku hanya ingin ngemil.
Ayam sudah dibumbui, tinggal digoreng.
Aku berencana untuk mengganti kentang dengan tahu.
Aku malas, jadi tidur dulu dalam buaian Unknown
Mortal Orchestra dan Tame Impala, sampai seekor kucing masuk dari jendela. Mau
tidak mau aku bangun untuk membukakan pintu kamarku, sehingga dia bisa keluar
untuk menyusui anak-anaknya.
Setelah galau sebentar aku pun menuju
dapur.
Ada enam sayap di panci, selebihnya cakar.
Aku ambil tiga, karena aku suka keseimbangan, untuk digoreng dengan minyak yang
sudah terpakai sebelumnya, karena aku suka hemat. Aku jauh dari wajan padahal,
sembari mengurus bumbu halus, tapi letupan minyak panas tetap mencipratiku.
Setelahnya aku goreng tiga kotak besar tahu—menyesuaikan
dengan jumlah sayap, juga mencuci bahan-bahan untuk bumbu halus. Resep bilang
tambahkan garam dan merica bubuk saat bumbu halus sudah ditumis, tapi aku butuh
pelicin untuk menggilas di cobek, jadi sekalian saja. Biar dikata bumbu halus,
tapi kupikir tidak perlu halus amat, lagipula aku bukan orang Minang.
Mensuwir-suwir ayam cukup menyenangkan,
sesekali aku menyuap potongan kering kulit ke mulut. Aku membuat kesalahan
dengan tahu. Sekiranya tahu, apalagi sebesar itu, dipotong kecil-kecil sejak
sebelum digoreng. Memotong tahu kecil-kecil setelah digoreng bikin potongan tidak
rapi, apalagi dalamnya masih rada lunak. Setelah dicampur dengan bumbu halus
nanti pasti hancur. Biarlah.
Sisa minyak untuk menggoreng ayam dan
tahu di wajan kukembalikan ke rantang, lalu aku ambil lagi beberapa sendok teh
untuk menumis. Sebentar saja minyak panas. Aku masukkan bumbu halus, kubuyarkan
dengan spatula kayu sampai lumayan harum. Aku tumpahkan potongan-potongan daging-kulit-mungkin-sedikit-tulang
ayam dan tahu ke wajan.
Hm… sudah tampak oke. Sambal goreng yang
pernah kubikin biasanya berhenti sampai tahap mencampur bumbu halus dengan
potongan lauk, tapi kali ini aku ingin mencoba hal baru, yang memang dititahkan
oleh resep, yaitu menambahkan santan…
…yang ternyata menghancurkan segalanya.
Di resep tertera 300 ml. Aku hanya akan
menuangkan 90 ml saja, sesuai yang tersedia di kulkas. Tidak kuduga 90 ml
sedemikian kental. Suwiran ayam bertabur butiran-butiran isi tahu yang dilumuri
dengan sobekan-sobekan merah nan seksi dari kulit cabai keriting mendadak bak
isi lambung yang tidak tercerna.
Aku lari keluar dapur untuk mengambil
segelas air dari dispenser, untuk kutuangkan ke adonan lembek itu. Masukkan air asam jawa. Masak sampai meresap.
Bagaimana dengan air mineral? Aku biarkan sampai meresap bagaimanapun juga.
Tergugu aku di muka wajan yang meruapkan
panas.
Air santan mineral itu benar-benar
meresap. Aku perhatikan lingkaran oranye kemerah-putihan itu perlahan menyurut,
hingga adonanku hampir persis seperti
mula tapi sayangnya tetap rada lembek. Aku aduk terus sambil bertanya-tanya, kapan kering, kapan kering, bisa enggak
kering? Ingin kulakukan terus sampai tercium gosong, tapi kucukupkan jua.
Adikku sudah masuk dan menanyakan kapan masakanku jadi, ingin segera makan dan
memang nyaris tidak ada lauk di meja makan.
Aku tuangkan “sambal goreng” rupa-rupa
itu ke mangkok. “Jangan lihat bentuknya,” kataku pada adikku, tapi lihatlah
dari rasanya yang sepertinya juga meragukan. Bagaimanapun aku belum makan nasi
dengan lauk sedari bangun pagi itu. Nasi masih panas, “sambal goreng” masih
panas. Ketika mamaku bertanya masakan apa itu,
aku ingin menjawab, pepes ayam-tahu tapi
isinya doang. Gundukan itu juga tampak seperti orak-arik, padahal aku tidak
membubuhkan telor setetespun. Ah entahlah.
 |
| Keliatan kayak nasi goreng... :-? |
Santan kental membuat orak-arik-atau-isi-pepes-padahal-sambal-goreng
itu terasa terlalu gurih, tapi sepadan jika dilahap bersama gumpalan nasi yang
manis-manis tawar. Enak juga, walau keasinan, tapi enak kok, cuman keasinan. Tapi
aku cukup puas.
Aku lanjutkan dengan menyendok bening bayam
bikinanku sendiri, yang sempat aku tidak berselera untuk memakannya. Adikku yang
lain lagi bilang kalau rasa masakanku tersebut biasa, yang malah kusyukuri,
ketimbang “keasinan”, atau “enggak enak”, atau “memuakkan”, ya kan? Setelah
kucicipi sendiri ternyata rasanya tidak seasin yang kukira. Cukup. Walau tidak
manis juga. Tapi cukup.
 |
| Wah... (pas mau ambil ternyata) tinggal dikit! Sepertinya lumayan laku... |
Lumayan, untuk ukuran orang yang biasa
makan seadanya.
Ingin kuteriakkan, (calon) ibu rumah tangga, BISA! Tapi sepertinya perjalanan masih
jauh.