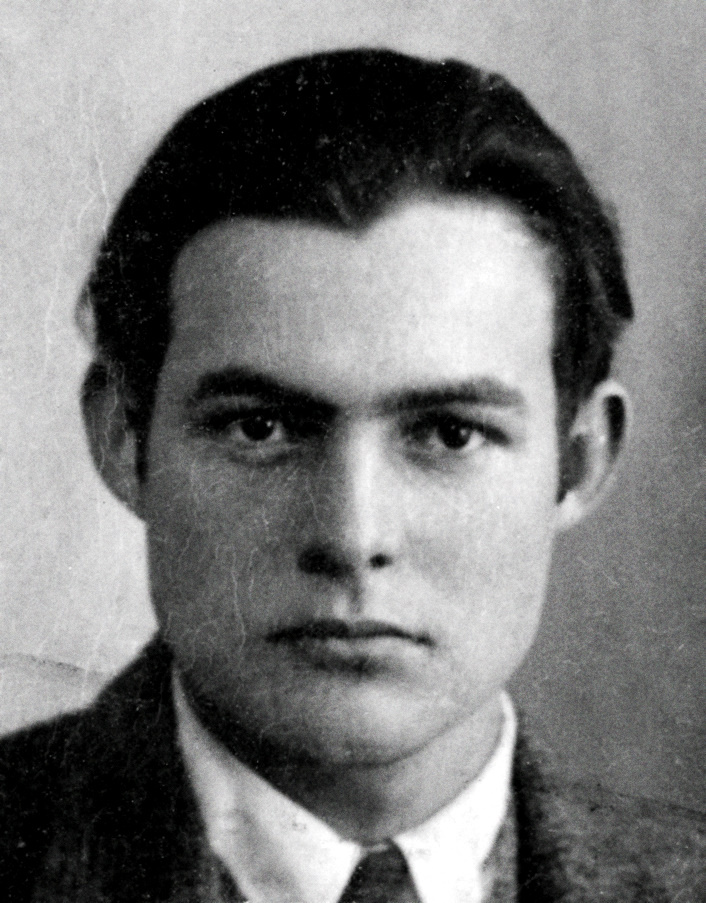 |
Potret Hemingway yang pernah saya
|
Ernest Hemingway sepertinya salah satu penulis Amerika Serikat paling
kesohor, termasuk di Indonesia. Banyak karyanya yang sudah diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia. Salah dua di antaranya yang saya sudah baca adalah
kumpulan cerpen Salju Kilimanjaro
serta novel Pertempuran Penghabisan.
Keduanya diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia, dan boleh dipinjam dari
perpustakaan universitas asal kartu anggotanya masih valid. Jujur saja, secara
umum pembacaan keduanya tidak membekas bagi saya. Padahal, Hemingway, lo.
Pengarang termasyhur! Kurang hebat apa dia? Boleh jadi karena tiga faktor: (1)
Gaya penulis; (2) Terjemahan; (3) Dan pastinya, rendahnya daya tangkap pembaca
(ehm). Mengenai gaya penulis, Hemingway dikenal dengan gayanya yang objektif
serta menerapkan prinsip “gunung es”, yakni: apa yang disuguhkan pada pembaca
itu baru 1/8 bagian daripada maksud pengarang—selebihnya ditenggelamkan di
bawah permukaan. Pembaca mesti berupaya lebih untuk dapat memahami makna
cerita. Mengenai terjemahan, saya tidak hendak mempermasalahkannya sih lagipun
dalam catatan saya memang tidak ada keluhan soal itu. Nah, mengenai rendahnya
daya tangkap pembaca inilah yang bikin faktor pertama dan kedua jadi tiada
artinya, ha-ha-ha. Karena itulah, catatan pembacaan ini ditulis untuk
dipergunakan dengan sebaik-baiknya. (?)
 |
| Sumber |
Catatan pembacaan saya atas Salju
Kilimanjaro bertanggal “181107”. Terutama saya menyalin ciri-ciri daripada
gaya kepenulisan Hemingway (dalam pengantar yang ditulis oleh Melani Budianta)
yang saya rasa menggugah. Adapun komentar saya terhadap cerpen-cerpen dalam
kumpulan itu sendiri cuman begini:
Cerita-cerita yang di tengah
itu kadang agak enggak jelas maksudnya apa, terutama Father and Son.
Salju Kilimanjaro (√)
Tempat yang Bersih dan Tenang
(gitu deh)
Sehari Menunggu Maut (ini nih,
lucu punya, paling kusuka)
Penjudi, Perawat, dan Radio
(lumayan)
Ayah dan Anak (hh)
Di Negeri Asing (hm)
Pembunuh Bayaran (lumayan)
Goncangan Jiwa Seorang Berkas
Sedadu (yang mana ya?)
Lima Puluh Ribu Dolar (ah,
enggak begitu…)
Kebahagiaan Hidup Francis
Macomber yang Singkat (butuh banyak lembar untuk membangun suasana, tapi
akhirannya oke juga)
Mohon dimaklumi. Pada masa itu saya baru memulai kebiasaan menuliskan pembacaan.
Peace.
 |
Kover Pertempuran Penghabisan
(alias A Farewell to Arms edisi Indonesia) ada beberapa versi. Sepertinya saya baca yang kovernya ini. Sumber. |
Bagaimanapun dalam catatan pembacaan karya Hemingway berikutnya, Pertempuran Penghabisan, yang bertanggal
“051208”, saya mengatakan kalau saya terkesan dengan Salju Kilimanjaro walau ada beberapa cerpen di dalamnya yang saya
tidak mengerti, dan akibatnya saya “sempat menjadikan Hemingway sebagai penulis
favorit…” (O_o). Tapi setelah Pertempuran
Penghabisan, saya “enggak bisa lebih lama mempertahankan itu.” (ah, labil!)
Saya menulis: “…ceritanya… kurang gimana gitu. … aku enggak menangkap esensi
lain selain perdamaian itu. … bukan novel yang bisa aku rekomendasikan…” Salju Kilimanjaro masih mending.
Begitulah. Lima tahun berselang. Kali ini saya dihadapkan pada cerpen “Hills
Like White Elephants” yang dirilis pada 1927. Teks dalam bahasa Inggris bisa
diakses di sini.
Terjemahan cerpen ini dalam bahasa Indonesia bisa ditemukan dalam buku Antologi Cerpen Nobel (ed. Wendoko) yang
diterbitkan oleh Penerbit Bentang—cetakan yang ada pada saya adalah yang
pertama, Mei 2004—juga di Fiksi Lotus. Pertama-tama,
saya membaca cerpen ini sekali dalam teks bahasa Inggris. Pembacaan pertama
dalam bahasa Inggris biasanya tidak langsung mengena, buat saya. Khusus untuk “Hills
Like White Elephants”, kendati bahasanya cukup simpel dan kesannya pun cair
karena didominasi oleh percakapan, saya masih belum dapat menangkap seketika
masalah apa yang dikemukakan.
Jadi ada sepasang laki-laki dan perempuan di sebuah bar di area stasiun. Mereka
tengah menunggu kereta dari Barcelona yang menuju ke Madrid. Yang laki-laki
berasal dari Amerika sedang yang perempuan tidak disebutkan dari mana, namun ia
dipanggil “Jig” dan tidak mengerti bahasa setempat. Yang laki-laki tampaknya
lebih tahu mengenai berbagai hal daripada yang perempuan. Mulai dari minuman,
komunikasi dengan wanita setempat, sampai sesuatu mengenai operasi. Cuaca amat
panas dan di sekeliling area tersebut terdapat pemandangan alam. Menurut yang
perempuan, bukit-bukit di sekitar situ tampak seperti gajah-gajah putih. Namun
yang laki-laki tidak begitu terkesan, malahan membujuk yang perempuan untuk
mengikuti “operasi”. Yang perempuan merajuk, sementara yang laki-laki terus
mengkhawatirkannya. Pada akhirnya yang perempuan mengatakan kalau ia baik-baik
saja.
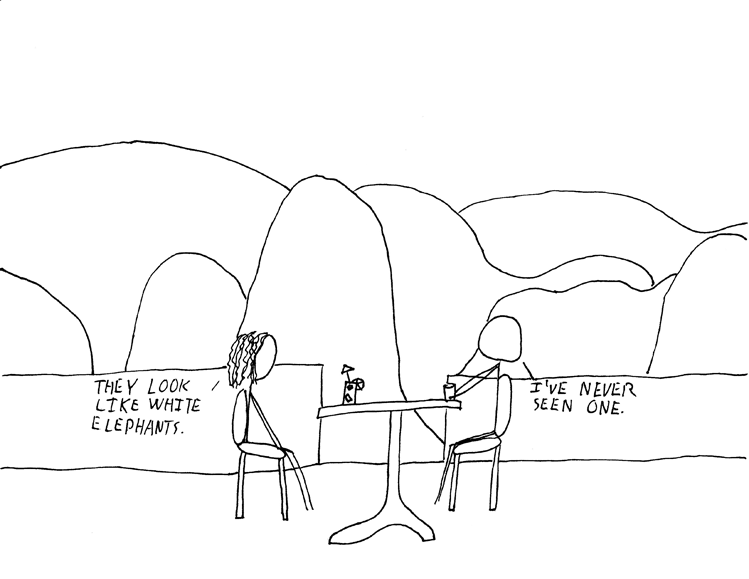 |
| Source |
Sampai mata saya menyoroti barisan pertanyaan di sesi TOPICS FOR
DISCUSSION AND WRITING. Ada kata “abortion” di sana. Kalau ada istilah momen “AHA”,
maka yang saya rasakan pada waktu itu adalah momen “OH”. Jadi ini cerita
tentang aborsi. Yang dimaksud yang laki-laki dengan “operation” adalah “abortion”.
Yang laki-laki membujuk yang perempuan untuk melakukan aborsi namun yang
perempuan keberatan makanya ia seperti merajuk.
Saya kemudian membaca terjemahan versi Antologi
Cerpen Nobel. Tentu saja tidak ada barisan pertanyaan sesudahnya. Kalau
saya membaca cerpen ini begitu saja dalam buku tersebut tanpa membaca
keterangan mengenainya, saya mungkin akan meninggalkannya begitu saja tanpa
kesan apa-apa. Tidak ada kata “aborsi”—“abortion”—sama sekali dalam teks. Dan
pembaca sebaiknya telah memiliki pengetahuan yang luas mengenai simbol karena
petunjuk mengenai aborsi ternyata terpendam dalam kiasan “bukit-bukit bagai
gajah putih”. Bahkan judul cerpen itu sendiri sudah mengindikasikan hal tersebut!
Dari keterangan soal aborsi itu kita tahu kalau yang perempuan jangan-jangan
hamil. Bukit-bukit yang tampak seperti gajah-gajah putih itu diibaratkan
sebagai payudara dan atau perut yang membesar (seperti gajah) ketika seorang
perempuan hamil. (Apalagi kalau perempuan tersebut adalah seorang kaukasoid—berkulit
putih.)
Terjemahan versi Fiksi Lotus agaknya mencoba untuk memperjelas sedikit
cara penyampaian dalam cerpen tersebut. (Walau pembubuhan judul yang tidak
sesuai dengan pengertian daripada judul aslinya itu jadinya malah mengaburkan “simbol”/”petunjuk”
yang padahal sudah diberikan sejak awal sekali.) Ditambah dengan adanya
poin-poin diskusi dan beberapa tanggapan, makna cerpen ini pun menjadi lebih
jelas lagi.
Yah, orang bisa menginterpretasikan apapun dari detail-detail yang
dianggapnya simbol. Itu pulalah yang membantu kita dalam memahami makna cerita.
Hemingway dipuja-puji karena gayanya yang teramat (kalau bukan
keterlaluan) efisien ini. Tapi bagi pembaca yang karakternya “malas berpikir”
macam saya, hasilnya hampir-hampir tidak menempel. Kurang menyentuh perasaan. Boleh
jadi gaya yang “objektif” itu pulalah yang menjadikannya terasa dingin, datar. Konon,
Hemingway itu “…tidak suka membuat kalimat atau paragraf yang terlalu panjang
karena khawatir pembacanya justru sulit menangkap/mengerti…” (sumber: sini). Selain
itu, menurut kutipan dalam pengantar Salju
Kilimanjaro, halaman xvii, “…karya Hemingway bisa digolongkan teks yang writersly, yang mengundang pembacanya
untuk ikut menulis, mengisi makna dan interpretasi di antara/di balik
baris-baris kalimat yang tersedia.” Tapi kok bagi saya kalimat atau paragraf
yang panjang itu lebih baik, asal jelas dan bahasanya sederhana, tidak
bertele-tele. Selain itu, masalah mengundang-untuk-ikut-menulis-atau-tidak itu
relatif sekali dan agaknya saya tidak perlu memperpanjang corat-coretan ini dengan
membahas soal itu. Bisa juga karena Hemingway mengusung tema-tema yang tidak
dekat dengan kehidupan saya, semisal asmara dan petualangan, makanya saya tidak
tergugah olehnya. (kering sekali hidupmu, day.)
Hemingway memenangkan penghargaan Nobel untuk kategori Sastra pada 1954. (Dan
tidak semua pemenang Nobel Sastra seterkenal dia, ya toh?) Maka, katanya begitulah yang dinamakan “karya
sastra”. Sebentuk tulisan yang digarap dengan “cantik” dan tidak cukup dibaca
sekali melainkan harus diiringi dengan perenungan.
Tidak hanya harus berpikir ekstra, pembaca kalau perlu juga mencari keterangan dari
manapun—komentar, kritik, biografi penulis, dan sebagainya—supaya lebih mudah
baginya memahami karya tersebut. Mencerdaskan, atau merepotkan? Kalau ingin
cerdas mesti rela repot kali ya… hm…[]

















