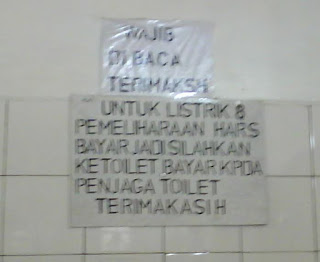Mama
menyarankanku untuk berkonsultasi dengan Pakde Iim. Putra tertua Kakek Burhan
itu selalu merupakan figur abang baginya. Maka aku melakukannya, sekalian
melepas kangen dengan Mbak An dan adik-adiknya. Saran Pakde Iim malah bikin aku
tambah rempong. Sudah persiapan BMC mulai menggeliat lagi, aku harus
mempelajari ilmu-ilmu sosial. Jadi, keputusannya, aku akan ikut jalur IPC.
Sore
berhujan itu, pertemuan sukarelawan BMC akan diadakan di salah satu kantin di
kampus Manda. Aku datang agak telat karena baru dari bimbel. Semakin mendekati
lokasi, semakin pasti penglihatanku akan sosok Manda yang sedang mengepul asap
rokok. Ia tidak menguncir rambutnya. Di sampingnya, Teh Icih duduk dengan
mengapit puntung rokok juga. Sepertinya perbincangan tentang BMC belum dimulai,
ini masih kumpul-kumpul para perokok.
Selain
mereka berdua, sudah ada tiga orang lagi yang datang. Kantin itu tidak bisa
dibilang sepi, tapi tidak terlampau ramai juga. Sebagian berada di sini
sepertinya hanya untuk berteduh atau asyik-asyikan dengan gerombolannya saja.
Manda
sepertinya sadar kalau aku agak kaget melihatnya merokok. Ia matikan ujung
puntungnya.
Setelah
aku benar-benar menyimak apa yang sedang orang-orang ini bicarakan, rupanya Teh
Icih sedang cerita soal para pengisi acara besok—terutama dari kalangan musisi
tenar. Sesekali ada gumaman heboh dari kami ketika band atau penyanyi yang
digemari telah dipastikan dapat tampil.
Selain
mengisi berbagai ruang publik dengan musik, BMC memiliki acara sampingan yang
akan dihelat di Sabuga. Jika acara lain merupakan pesta rakyat, alias gratis,
acara satu ini agak eksklusif karena harus bayar. Sengaja diadakan agar dana
tertalangi.
Teh
Icih sedang bingung karena ada beberapa musisi yang sukar dihubungi. Salah
satunya Ardian Hayyra.
Tersengat
aku mendengar nama itu.
“Teh,
Ardian Hayyra kenapa Teh?” tanya Manda.
“Kalau
untuk Kang Hayyra, ini juga lagi saya tanyakan sama Abah,” kata Teh Icih.
Manda
memandangku.
Kami tidak membicarakan itu lagi
ketika rapat sungguh-sungguh dimulai. Kami membicarakan langkah-langkah teknis
untuk mematangkan acara yang akan berlangsung dalam beberapa minggu lagi.
Bubar. Manda menyenggolku. “Om Yan
kenapa Be?”
Aku mengangkat bahu. Aku sendiri
menyadari bahwa beberapa bulan telah berlalu sejak takziah ibunya. Itulah kali
terakhir aku melihatnya. Setelah tidak berhasil menghubunginya ketika tanteku
habis melahirkan, aku coba meneleponnya sesekali. Namun jawabannya selalu sama,
sampai wanita di seberang sana bilang kalau nomor itu sudah tidak aktif.
Beritanya sebagai pendatang baru dalam belantika musik Indonesia pun sudah
tidak muncul lagi. Berita terakhir yang memuat namanya di media adalah berita
kematian ibunya.
Ia
seperti menghilang.
Seakan
aku juga telah lupa kalau ia pernah mewarnai hidupku, menghangatkan hari-hariku.
Apakah
ia masih bertemu dengan anak-anak Tante Ri? Dengan Tante Ri? Ah. Tidak patut
aku bertanya seperti itu. Aku sudah tidak pernah mampir ke Kedai Buncong lagi.
Sesekali aku masih bertukar sms dengan Vira. Aku katakan padanya kalau aku
sibuk menemani tanteku yang baru melahirkan. Juga persiapan ujian. Aku tidak
sekadar cari-cari alasan, itu memang benar.
Padahal
mereka pernah begitu baik padaku, sekarang terlupa begitu saja. Betapa tidak
tahu diri aku ini.
Dalam
perjalanan pulang, aku terkenang. Pada saat-saat di mana ia mengantarku pulang,
saat-saat di mana kami menghabiskan waktu di kafe ini, atau tempat anu, pada
cerita-cerita yang kami tukar, pada senyumnya, pada keinginannya yang
diam-diam… untuk jadi ayah.
Lalu
aku coba melacak beberapa media sosialnya. Tidak ada yang baru. Barangkali
bukan ia yang mengisi, bahkan.
Yah, aku kangen, Yah… tulisku. Kirim.
Lain
kali, aku coba mengetik surel untuknya. Aku kirimkan beberapa paragraf yang
berisi kabarku, minta ditukar dengan kabarnya.
Beberapa
hari kemudian, aku mengecek apakah ada balasan darinya atau tidak.
Aku
seperti melakukan hal bodoh.
“Ma,
ke mana Om Yan?” tanyaku akhirnya pada Mama.
“Lo,
kan Bibe yang suka ketemuan sama Om Yan?”
“Om
Yan bukannya selalu bilang sama Mama kalau mau ketemu aku?”
Mama
mengerjap-ngerjap. “Mungkin Om Yan udah balik Bibe.”
“Masak…
Kan dia bukannya mau ikut BMC Ma…”
“Aduh,
Mama enggak tahu… Mau ditanyain ke temen Mama?”
Mamaku
benar-benar menanyakannya pada Om Dedi. Om Dedi tidak tahu-menahu. Mamaku
menyarankanku untuk tanya pada Tante Zahra. Ah sudahlah, aku jadi malu.
Sepertinya hanya aku yang sungguh-sungguh merasa kehilangan. Lainnya biasa
saja. Mereka tidak bertemu Om Yan sesering aku.
Di
sela-sela jadwal bimbel yang memadat, kontras dengan jadwal sekolah yang melonggar,
aku sisihkan waktu dari mengasuh Kiran dan menemani tanteku. Aku ingin menapaki
jalan itu lagi. Jalan kelabu dalam benakku. Di mana aku menuju rumah itu, yang
dua kali dalam kunjunganku pintu sampingnya menyisakan celah. Kini tertutup
rapat. Bunga-bunga di halaman tampak menyambutku dalam dingin. Daun-daun kering
berbaring di teras bersaputkan debu-debu. Tak berpenghuni. Mati.
Aku
pulang ke rumah lalu mendengarkan ragam musik Ardian Hayyra. Aku masih tidak
bisa memahami mereka. Di mana penggubahnya sekarang? Sedang apa? Apakah ia
masih menemui kekasihnya? Jadi hubunganku dengannya hanya sampai yang kemarin
itu saja?
“Jadi
kamu udah enggak pernah kontak-kontakan sama Ardian Hayyra lagi Be?” tanya
Manda. Aku memboncengnya pulang setelah kami mengurus logistik untuk keperluan
BMC. Kami masih jadi tim. Dan kami netral satu sama lain, setidaknya begitulah
yang aku rasa.
“Enggak.”
“Di
acara yang di Sabuga entar dia katanya bisa hadir lo.”
“O
ya?” Punggungku mendadak tegak.
“Mau
tanya langsung sama Teh Icih?”
Aku
menggeleng. Tidak. Tidak perlu. Karena Om Yan sendiri yang meneleponku malam
itu. Aku penasaran apakah ia bisa membaca pikiranku dari kejauhan. Ia tidak
menggunakan nomor yang biasanya tidak bisa dihubungi itu.
“Om
Yan, ke mana aja?” tanyaku menahan harus sekaligus isak. Aku berkata begitu
pelan di tepi tempat tidur dengan pintu kamar tertutup. Aku tidak mau papaku
dengar.
Tawanya
masih renyah.
“Saya
di rumah keponakannya Abah Bibe… Di sini tenang sekali…” Ia menyebut sebuah
daerah di pinggiran Bandung. “Bambunya masih banyak… Kalau pagi saya suka
jalan-jalan ke sawah, liat airnya masih jernih sekali. Kali juga masih ada
airnya. Kadang-kadang saya main ke rumah penduduk, cuman buat minum teh aja…
Kalau bisa telepon Bibe pagi-pagi mah, bisa kedengaran suara burung pagi-pagi
ramai sekali…”
Sekarang
saja sudah terdengar derik jangkrik mengawang-awang sebagai latar suara Om Yan.
“Ngapain
di sana?” tanyaku.
“Persiapan
Bibe…”
Biar
diembeli “sampingan”, acara di Sabuga akan berlangsung meriah. Para musisi Sunda
akan jadi poros. Sebagai musisi pendamping, yang sekaligus menjadikan ini
sebagai proyek, Om Yan tampak menghadapinya dengan serius. Ia cerita, di desa
tersebut para musisi yang akan berkolaborasi dengannya berkumpul untuk
menerjemahkan orkestra alam jadi harmoni calung serta kacapi suling. Ini
seperti perlawatan yang biasa Om Yan lakukan ketika ingin menghayati ragam
musik langsung dari sumbernya. Tapi kali ini pakai acara gotong piano segala.
“Om
susah banget dihubungin..” masih aku mengeluh. “Jadi sekarang Om udah ganti
nomor jadi yang ini?”
“Enggak
Bibe, ini bukan nomor saya.”
“Aku
juga kirim e-mail ke Om Yan…”
Tapi
ia tidak dengar. Ucapanku tadi tertimpa ucapannya, yang langsung kusimak begitu
aku selesai berkata-kata. “Bibe, maaf, saya boleh minta tolong Bibe?”
“Iya
Om?”
“Begini…
Bibe masih suka main ke rumah Tante Ri?”
Seperti
ada yang berdentum di dalam dadaku. “Udah jarang Om…”
Aku
tidak segera mendengar jawaban. Agak lama, sampai ia berkata lagi dengan
lembut, “Bibe mau ketemu Tante Ri lagi?”
Aku
terpana. “..i… ya… Kenapa Om?”
“Ah,
iya, kalau boleh… Bibe bisa ajak Tante Ri ke acara BMC yang di Sabuga itu?”
“Oh…”
“Tolong….”
Suaranya tertahan sejenak. “…dipastikan Tante Ri bisa datang ya Bibe. Bibe bisa
kasih langsung ke Tante Ri?”
“Insya
Allah Om, saya usahakan.”
“Nanti
saya pesankan ke Teh Icih. Nanti Bibe tolong ambil ke Teh Icih ya…”
“Iya
Om.”
“Terima
kasih Bibe. Kita ketemu di Sabuga besok ya?”
“Kapan?”
“Iya,
besok, pas acara. Bibe masih jadi panitia kan?”
“Iya
Om.”
“Terima
kasih ya Bibe.”
“Iya
Om.”
Otakku
berpikir cepat bagaimana menyampaikan titipan itu pada Tante Ri dengan aman,
tanpa harus diketahui anak-anak Tante Ri atau siapapun.
“Baik
Bibe…”
“Om.”
“Ya?”
“Ada
nomornya Tante Ri?”
“Ah.
Sebentar saya cari dulu.”
***
Tante
Ri mengajakku bertemu di suatu mal, di Bandung tentu saja, pada akhir minggu,
tepatnya di suatu gerai makan yang tenang dan relatif sepi. Ia datang lebih
dulu dari aku. Ia mengambil tempat di pinggir jendela, semakin terpencil,
sendirian.
Ia
menjaga senyumnya, tapi matanya tidak. Aku tidak bisa membaca apa yang tersirat
di sana. Jelas suasana hatinya tidak baik, aku menduga-duga.
“Gimana
kabar Ari sama Vira, Tante?”
“Baik.”
Sorot sendu itu jadi agak kabur.
“Ari
mau ngelanjutin ke mana Tante?” Aku tidak berbasa-basi. Aku memang sungguh
ingin tahu nasib bocah tampan, cerdas, soleh, dan humoris tapi asosial, arogan,
dan daya motoriknya hanya canggih di jemari itu.
“Pinginnya
dimasukin pesantren.”
“Hah?”
“Dari
kecil emang anak itu rada istimewa…”
“Pesantren
mana Tante?”
Ada
sebuah pondok pesantren modern terkenal di pelosok Jawa Timur.
Serius,
anak manja itu bisa tahan hidup keras ala santri begitu? Apakah ia bisa hidup
sehari saja tanpa pegang joystick?
“Vira
juga mau masuk SMP ya Tan?”
“Iya.
Paling ngelanjutin ke yayasan yang sama aja…”
Aku
mau menghabiskan malam dengan gadis kecil itu lagi kalau kakaknya benar-benar
jadi mondok di pesantren.
Kami
diam beberapa lama.
“Jadi…
Gimana kabarnya Yan?” tanyanya.
Sebetulnya
aku agak kaget juga mendengar jawaban itu.
“Aku…
udah jarang ketemu sama Om Yan lagi, Tante. Kemarin cuman lewat telepon aja.
Sekali.”
“Oh…”
“Terakhir
kali ketemu pas… ke takziah ibunya.” Dan aku melihatmu menangis.
Ia
menunduk sebentar. Kepalanya naik lagi dengan pandang menerawang. “Ya.” Ia
menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya. “Ini memang berat buat
dia.” Tante Ri mencoba tersenyum lebih
lebar. “Yan itu… dekat sekali dengan ibunya.”
Ia
masih menyimpan foto ibunya waktu muda di dalam dompet. Ia menurut ketika
ibunya ingin ia sekolah di luar negeri. Setelah gemilang, ia ambil cuti panjang
untuk menemani hari tua sang ibu.
Dan
tidakkah sekilas Tante Ri tampak mirip dengan ibunya Om Yan?
Tante
Ri kira Om Yan sudah tidak di Indonesia lagi.
“Enggak,
Tante. Kan ada… itu… Bandung Musical City.” Aku jelaskan padanya ihwal helatan
warga musisi Bandung tersebut.
“Iya…
Aku kira itu sudah selesai. Dia sering bolak-balik ke… “ Ia menyebut nama desa
yang kemarin Om Yan sebut di telepon.
“Belum
Tante.”
Ia
tidak berkata-kata lagi. Senyumnya tidak mampu memudarkan gundah. Aku
benar-benar penasaran bagaimana hubungan di antara kedua orang ini. Akhirnya
aku menyerahkan amplop berisi tiket itu padanya. Ia mengintip isinya. Ia hanya
mengambil satu. “Saya datang sendiri aja,” katanya. Ia mengembalikan lainnya.
Kami
tidak bercengkerama lebih lama lagi.
Sejujurnya,
aku agak iba melihatnya.
Setelah
itu, hari-hariku berlalu bagai angin ribut. Sekolah sudah tidak lagi
mengusikku, namun jadwal bimbel tidak lagi bisa kulewatkan. Aku masih harus
belajar tambahan agar sukses di jalur IPC. Belum lagi persiapan BMC dan
kecenderunganku untuk mengambil alih pekerjaan orang lain. Ketika aku sudah
diberi tugas untuk menyiapkan satu tempat saja, aku mencampuri persiapan di
tempat lain. Yang mengingatkanku bahwa
itu bukan bagianku adalah ketidakhadiran Manda. Kami kan satu tim. Ya. Dan
Manda bukan orang yang suka mengambil banyak peran. Ia beda denganku.
Yang
aku sedihkan adalah ujian masuk perguruan tinggi terselip di antara serangkaian
acara BMC. Mama mewanti-wanti agar acara BMC tidak sampai menggagalkan
kesempatan yang menentukan masa depanku ini. Aku jadi tidak bisa lihat
penampilan Om Yan secara cuma-cuma di salah satu ruang publik. Katanya ia bakal
memainkan pianika bersama beberapa musisi muda.
Tapi
untungnya, acara yang di Sabuga dihelat sesudah ujianku.
Malam
itu, aku jadi petugas pengarah. Aku menggunakan kaos BMC dan mengalungkan tanda
pengenal di leher. Aku mondar-mandir di dalam gedung pertunjukan untuk membantu
orang-orang menemukan tempat duduk sesuai nomor yang tertera di tiketnya.
Sekilas aku melihat sosok jangkung nan necis mengintip dari pintu di sisi
panggung. Aku menoleh beberapa kali untuk memastikan kalau aku tidak salah
lihat. Langsung kutinggalkan tugasku.
“Om
Yan!” teriakku.
“Hei
Bibe…” Ia merunduk.
Aku
terbenam dalam pelukannya. Tersesap harum yang kurindu.
“Om…
Aku kangen…” kataku. Aku sungguh-sungguh.
Ia
mengelus kepalaku. Aku merasa kenyamanan kembali merengkuhku.
“Kapan
kita jalan-jalan lagi Om?” tanyaku. Bukan basa-basi.
Ia
sudah berdiri lagi. Beberapa lama kami hanya berpandangan saja. “Kapan-kapan
Bibe, main ke rumah Om ya?”
“Rumah
Om yang…” Aku tidak yakin rumah itu masih berpenghuni.
“Bukan.
Rumah yang satu lagi.”
“Di
mana?”
“Boston.”
“Jauh.”
“Pokoknya
Om tunggu Bibe di sana.”
Serasa
ada harapan yang ia jatuhkan padaku.
“Aku
belum lihat Tante Ri, Om.”
“Enggak
apa-apa. Nanti juga datang.”
Aku
tahu ia sendiri tidak pasti.
“Sekalian
saya juga mau pamit sama Bibe.”
Besok
ia tidak lagi di menjejakkan kaki di tanah ini.
Keluarga
adiknya juga datang ke mari untuk menyaksikan. Aku dikenalkan pada mereka.
Namun para anak lelaki terlalu bandel untuk diam dan mengulurkan tangan.
Tante
Ri datang ketika lampu-lampu sudah digelapkan. Dengan sigap aku menyambutnya.
Memang mataku sedari tadi mengawasi setiap paras yang masuk ke mari. Sudah
was-was saja aku kalau-kalau ia tidak memanfaatkan tiket gratisannya.
Sembari
membimbingnya menuju bangku di deretan terdepan, aku sampaikan amanat Om Yan.
“Tante, entar setelah Om Yan penampilan yang pertama, ditunggu di….”
Setelah
penampilan Om Yan yang pertama, aku menyelinap lewat pintu lainnya—yang jelas
tidak sama dengan Tante Ri. Beberapa kali survei, gladi bersih, dan menyiapkan
tempat ini untuk pertunjukan, aku sudah menentukan beberapa sudut di mana aku
bisa mengintip tanpa terlihat dari titik mereka bertemu.
Tidak banyak. Tidak lama. Aku hanya lihat
sang pria bicara pada sang wanita. Sang wanita mengusap matanya. Tidak dengar
apa yang ia katakan. Aku tidak bisa menyimak lebih lama. Seseorang memanggilku
dan aku tidak ingin orang tersebut mengetahui ini. Jadi aku segera pergi.
Di tengah malam sehabis pertunjukan
itu, Om Yan pergi dari Sabuga bersama keluarga adiknya kok, tidak dengan Tante
Ri.