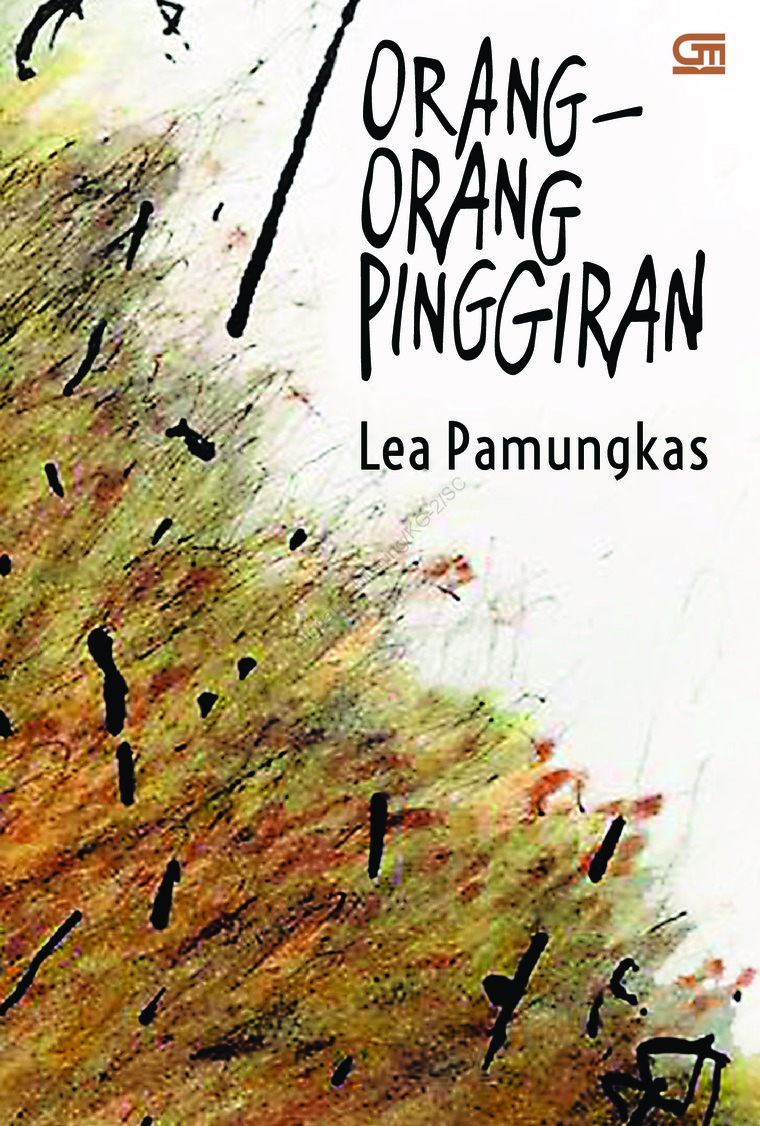 |
| Gambar diambil dari Gramedia Digital. |
Acara serupa sebelumnya telah diadakan di Universitas Leiden dan Universitas Padjajaran.
Acara di Gedung YPK ini dibuka dengan penampilan dari Muktimukti berupa musikalisasi salah satu cerpen dalam buku, diiringi dengan gitar.
 |
| Dari tempat saya duduk, kiri ke kanan: Kang Opik sebagai moderator, Bu Lea sebagai penulis, Pak Ari sebagai pembicara pertama, dan Pak Hikmat sebagai pembicara kedua. |
Moderator kemudian mempersilakan tiap-tiap pembicara untuk memaparkan pembahasannya mengenai buku. Penulis sendiri baru angkat suara pada sesi berikutnya, yaitu untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari peserta.
Pembicara pertama yaitu Pak Ari Jogaiswara A, dosen Sastra Inggris Universitas Padjajaran. Beliau memulai dengan membahas judul, yang langsung menyatakan wacana yang hendak diangkat. "Orang-orang pinggiran" yang diangkat dalam buku ini pun mencakup berbagai isu, entahkah gender, ekonomi, sampai imigrasi. Beliau menerangkan bahwa kesusasteraan memang ruang bagi orang-orang pinggiran, sebab bidang-bidang lain pada tidak berkenan menerimanya. Tema yang lain dapat diangkat dalam berbagai bentuk ekspresi lainnya, katakanlah entertainment (mungkin yang dimaksud di sini adalah tentang sosok-sosok populer), tapi "sastra" selalu bicara tentang orang pinggiran.
Mengenai konten, cerpen-cerpen dalam buku ini walaupun ditulis dalam bahasa Indonesia tapi tidak selalu berbicara tentang keindonesiaan. Sebagian cerpen mengisahkan tentang orang-orang dari negara lain yang hidup di negara lain pula, semacam yang telah diinisiasi oleh Budi Darma dalam Orang-orang Bloomington dan Olenka. Karena keahlian Pak Ari Sastra Inggris, beliau membandingkankannya dengan tren yang ada di dunia Sastra Inggris sendiri, yaitu pergeseran dari Sastra Inggris ke Sastra Berbahasa Inggris. Maksudnya, Sastra Inggris tidak lagi hanya meliputi penulis-penulis dari Inggris Raya atau Amerika Serikat yang menceritakan tentang kehidupan di tempat mereka, tapi juga mencakup penulis-penulis dari negara mana pun--katakanlah yang bekas koloni Inggris seperti India, Ghana, dan Jamaika--yang menulis dalam bahasa Inggris. Karena isi kumcer ini yang tidak melulu keindonesiaan, maka buku ini secara keseluruhan lebih tepat dikatakan sebagai Sastra Berbahasa Indonesia ketimbang Sastra Indonesia.
Nantinya, penulis menambahkan bahwa ketika buku ini dibahas di Universitas Leiden, ada juga profesor yang mempersoalkan hal serupa: apakah kumcer ini Sastra Indonesia atau Sastra Berbahasa Indonesia? Malah, di Belanda, telah berkembang suatu genre baru bernama Sastra Migran. Pengelompokkan sastra tidak lagi berdasarkan wilayah, tapi tema. Toh belakangan ini, sastra dalam bahasa mana pun tampaknya cenderung mengangkat tema-tema yang serupa, misalnya tentang kehidupan di kota besar, radikalisme, lingkungan hidup, dan sebagainya. Sastra tidak lagi punya batasan.
Pak Ari lalu membahas tentang penulis, yang lebih produktif sebagai jurnalis ketimbang pengarang fiksi. Cerpen-cerpen ini ditulis dalam rentang 1994-2019, dengan jeda-jeda yang lumayan lama antar tiap karya berikut latar yang berbeda-beda. Maka penulis baru menuliskan ceritanya ketika sudah siap, atau saat kata-katanya telah hadir. Gagasannya tidak keluar begitu saja, isinya tidak latah, tapi diperam terlebih dahulu. Memang itulah bedanya antara jurnalistik dan sastra. Karya jurnalistik mesti ditulis sesegera mungkin setelah peristiwanya terjadi, adapun sastra memerlukan perenungan serta diperbincangkan atau didialogkan dengan gagasan-gagasan lain terlebih dahulu.
Dalam suatu kumpulan cerita yang ditulis satu orang, tidak terhindarkan ada pola. Tapi karena cerpen-cerpen dalam buku ini ditulis dalam rentang-rentang yang cukup panjang, maka ada keragaman "musikalitas bahasa". (Saya beri tanda kutip karena enggak begitu mengerti maksudnya, hahaha. Ampun, pak dosen
Ada satu cerpen dalam buku ini, "Anak Kami Si Pelaku", yang dari judulnya saja kita sudah dapat mengira-ngira isi cerita. Judul cerpen ini rupanya mirip dengan judul cerpen seorang penulis Iran, yang mirip dengan judul cerpen seorang penulis Yahudi AS. Beliau menamakan model ini sebagai cerpen estafet: bagaimana satu cerpen terinspirasi oleh cerpen lain dan cerpen-cerpen serupa akan terus tercipta selama permasalahannya masih ada. Kalau boleh dikaitkan, mungkin ini agak-agak seperti cerpen "Referential" Lorrie Moore (terjemahan Indonesia) yang menyerupai cerpen "Symbols and Signs" Vladimir Nabokov--setidaknya ini satu contoh semacam yang pernah saya temukan sendiri.
Selain itu, Pak Ari juga menerangkan bahwa karya fiksi bergerak dari dua modus, yaitu "melihat" serta "bertutur". (Di sini, lagi-lagi saya enggak mengerti.)
Bagaimanapun, penulis punya kemampuan untuk melihat yang jauh secara dekat. Secara keseluruhan, buku ini "empowering".
Selanjutnya, Pak Hikmat Gumelar membuka gilirannya dengan mengangkat soal perspektif poskolonial. Kalau boleh saya jabarkan sedikit dari yang saya tangkap di sini (yang bercampur dengan sedikit pengetahuan saya sendiri), agaknya tentang bagaimana kita selaku pembaca Indonesia--yang notabene negara bekas jajahan--melihat Eropa secara tinggi. Padahal di Eropa sendiri, secara keseluruhan, ada pula masyarakat yang terpinggirkan--katakanlah mereka yang berasal dari Eropa Timur. Maka kumcer ini menunjukkan suatu perspektif unik mengenai Eropa.
Oke, mungkin bukan itu yang Pak Hikmat maksudkan.
Pak Hikmat juga mengutarakan tentang kekhasan bentuk cerpen, yang acap kali dilecehkan sebagai sekadar ringkasan novel atau latihan menulis novel. Padahal cerpen itu juga suatu penghormatan terhadap kemanusiaan dengan formulanya yang "mulai dari tengah, akhiri dari tengah". Mungkin, maksudnya, kalau dibandingkan dengan roman atau novel yang cenderung mencakup rentang waktu yang lebih panjang atau sangat panjang (dari lahir sampai mati) dalam kehidupan tokoh-tokohnya, cerpen hanya mengambil peristiwa yang penting-penting saja--yang terjadi di sela-sela atau tengah-tengah sepanjang kehidupan seorang manusia.
Betul enggak sih, Pak? #keplak
(Nantinya, Pak Ari menambahkan sedikit soal cerpen yang rupanya berusia lebih muda daripada novel. Padahal novel saja sudah "novel"--dalam bahasa Inggris berarti "baru". Mungkin, karena perkembangan zaman, maka orang semakin sedikit atau malah tidak punya waktu untuk membaca sehingga bentuk narasi semakin singkat saja. Bahkan sepertinya sekarang pun cerpen sudah ketinggalan zaman.
Beliau juga menyebutkan tentang pandangan seorang sastrawan dunia ternama asal Tiongkok, Gao Xingjian, tentang seni fiksi yang memerlukan ketekunan menyimak hidup. Kemampuan ini merupakan kendaraan penulis fiksi dalam menemukan suara kemanusiaan.
Atau kira-kira begitulah.
Beliau juga menyinggung tentang Elena Ferrante yang tidak mau mengungkap identitas aslinya, sebab menurutnya, penulis tidaklah penting--seolah-olah biarlah karyanya saja yang sudah cukup berbicara. Penulis Italia ini juga dikenal sulit memberikan izin untuk mengadaptasi karyanya ke layar, hingga belakangan HBO berhasil mendapatkannya. Sepertinya, ia tidak mau karyanya sekadar jadi "film", tapi mesti dapat menangkap "musikalitas" atau apa dari karyanya, aduh saya pusing, sepertinya Elena Ferrante penulis militan yang tahu benar tentang sastra--sebaiknya saya coba baca karya-karyanya suatu saat biarpun hanya dalam terjemahan bahasa Inggris.
Orang-orang pinggiran adalah radar perubahan sosial.
Pak Hikmat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan buku yang berisi sepuluh cerpen ini merupakan "kitab kecil yang bermakna besar".
Kemudian, dibukalah sesi tanya jawab. Seperti biasa, tiga penanya diberikan kesempatan.
Penanya pertama memberikan pendapatnya mengenai kumpulan cerpen ini. Yang saya tangkap: kita semua adalah orang-orang pinggiran.
Penanya kedua menanyakan hal teknis: 1) Urutan cerpen dalam buku berdasarkan apa?; 2) Siapa yang menentukan judul dan kenapa diberi judul begitu?
Yang nantinya dijawab oleh penulis: 1) Berdasarkan pada waktu cerpen diterbitkan atau diciptakan. (Cerpen-cerpen ini sebelumnya sudah pada pernah dimuat di Kompas.); 2) Ditentukan oleh penulis sendiri berdasarkan pada substansi umum cerpen-cerpennya.
Penanya ketiga memberikan tanggapannya akan salah satu cerpen, yang menurutnya menunjukkan kemampuan untuk dapat membalut peristiwa yang sangat emosional sehingga menjadi tidak terasa emosional.
Dalam sesi ini pun penulis mendapat kesempatan untuk berbicara banyak, walaupun tidak panjang lebar. Setelah mendengarkan berbagai tanggapan atas karyanya, beliau mengungkapkan betapa ada hal-hal yang disembunyikan atau bahkan tidak disadari oleh dirinya sendiri yang dapat terlihat oleh orang lain.
Beliau juga menceritakan sedikit tentang proses kreatifnya, misalkan untuk cerpen "Anjing yang Meleleh di Ingatan Sotera". Cerpen ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang ayahnya mengalami gangguan jiwa setelah menjadi korban peristiwa Chernobyl. Ada ketakutan bahwa dirinya juga akan menjadi gila, tapi perasaan itu tidak tampak. Kisah hidupnya ia ceritakan dengan wajah yang datar saja. Penulis menghubungkannya dengan perilaku keseharian kita sendiri--manusia pada umumnya--dalam bermedia sosial. Di balik emotikon-emotikon nan ekspresif, ada wajah datar dan kita bisa memutuskan pembicaraan dengan siapa saja kapan saja kita mau.
Masih ada beberapa peserta lainnya yang angkat tangan, meminta kesempatan untuk memberikan pertanyaan atau pendapat. Tapi, sayang, waktu terbatas.
Acara diskusi pun ditutup, tapi rupanya masih ada pertunjukan-pertunjukan lainnya. Kedua pertunjukan ini sama-sama mengambil inspirasi dari kumcer.
Pertunjukan pertama dibawakan oleh kelompok teater Pak Ari, dibuka dengan seorang pemuda duduk menyanyikan lagu "Stay" dari U2 diiringi petikan gitar. Pada layar di belakangnya pun terpampang video yang menampakkan wajah seorang perempuan yang lalu bermonolog. Itulah yang unik dari pertunjukan ini. Penggunaan media video call menunjukkan adanya jarak antara yang dilihat dan melihat, seperti yang terkesan dari cerpen yang diangkat, yaitu "Setengah Hari Hidup Dita". Dita bekerja sebagai pembersih hotel di Belanda. Tiap hari ia membersihkan sampah-sampah yang ditinggalkan oleh para tamu di kamar. Dari sampah-sampah itu ia dapat "melihat" kehidupan tiap-tiap tamu. Tapi tamu-tamu itu sendiri tidak dapat melihat dia. Oh, ya, Dita juga suicidal.
Ada kutipan yang menarik: "Kuat enggak kuat, sama aja."
Pertunjukan terakhir merupakan kolaborasi antara Pak Hikmat dan Pak Isa Perkasa. Di latar ditaruh lukisan besar yang menampakkan seraut wajah. Sementara Pak Hikmat membacakan cerpen pilihannya dari buku penulis, Pak Isa menambahkan warna-warna pada lukisan itu: merah, biru, hijau, dan seterusnya.
 |
| Pembacaan cerpen diiringi pencoret-coretan lukisan. |
Sementara itu, di luar turun hujan deras.








Tidak ada komentar:
Posting Komentar