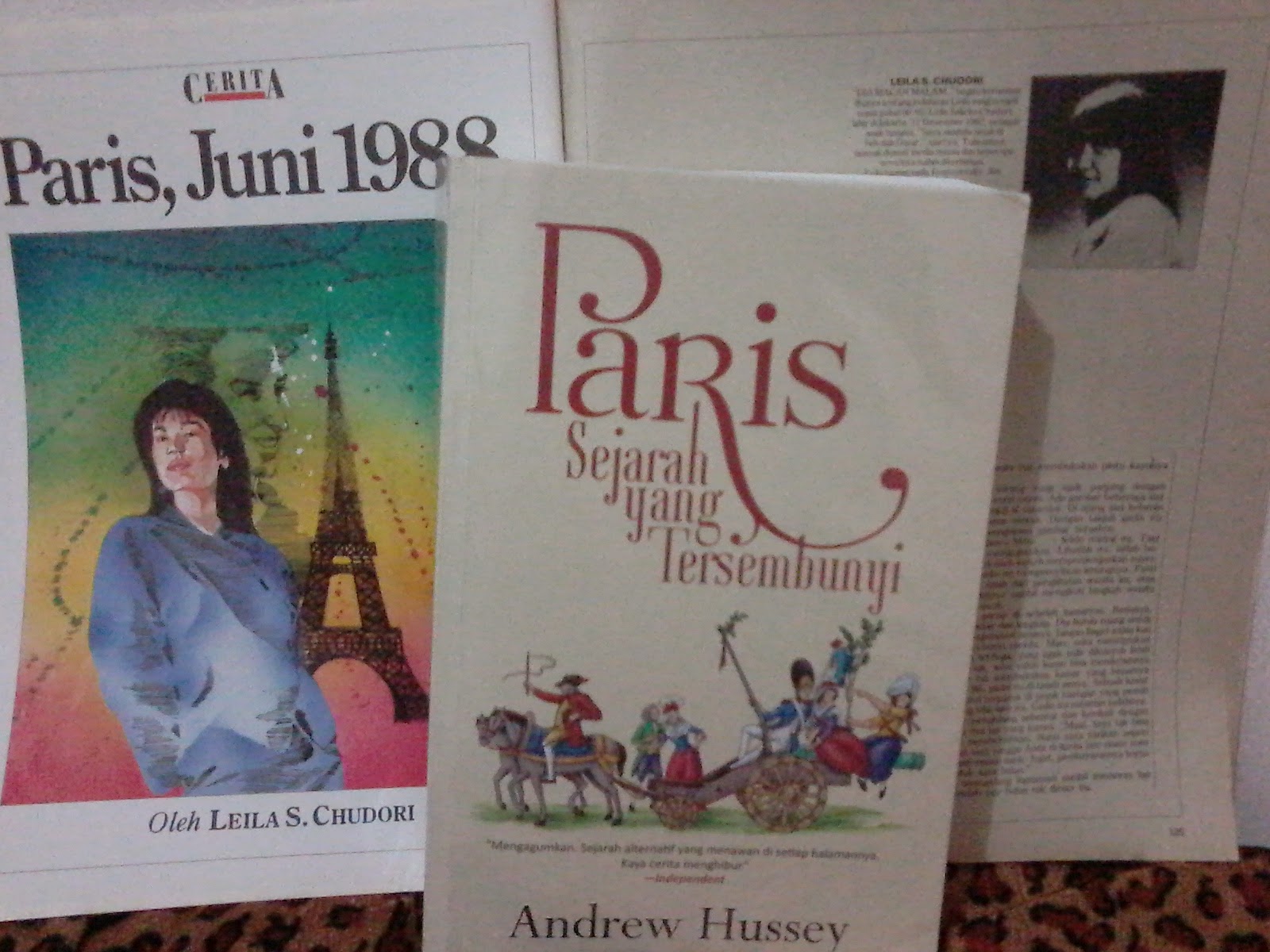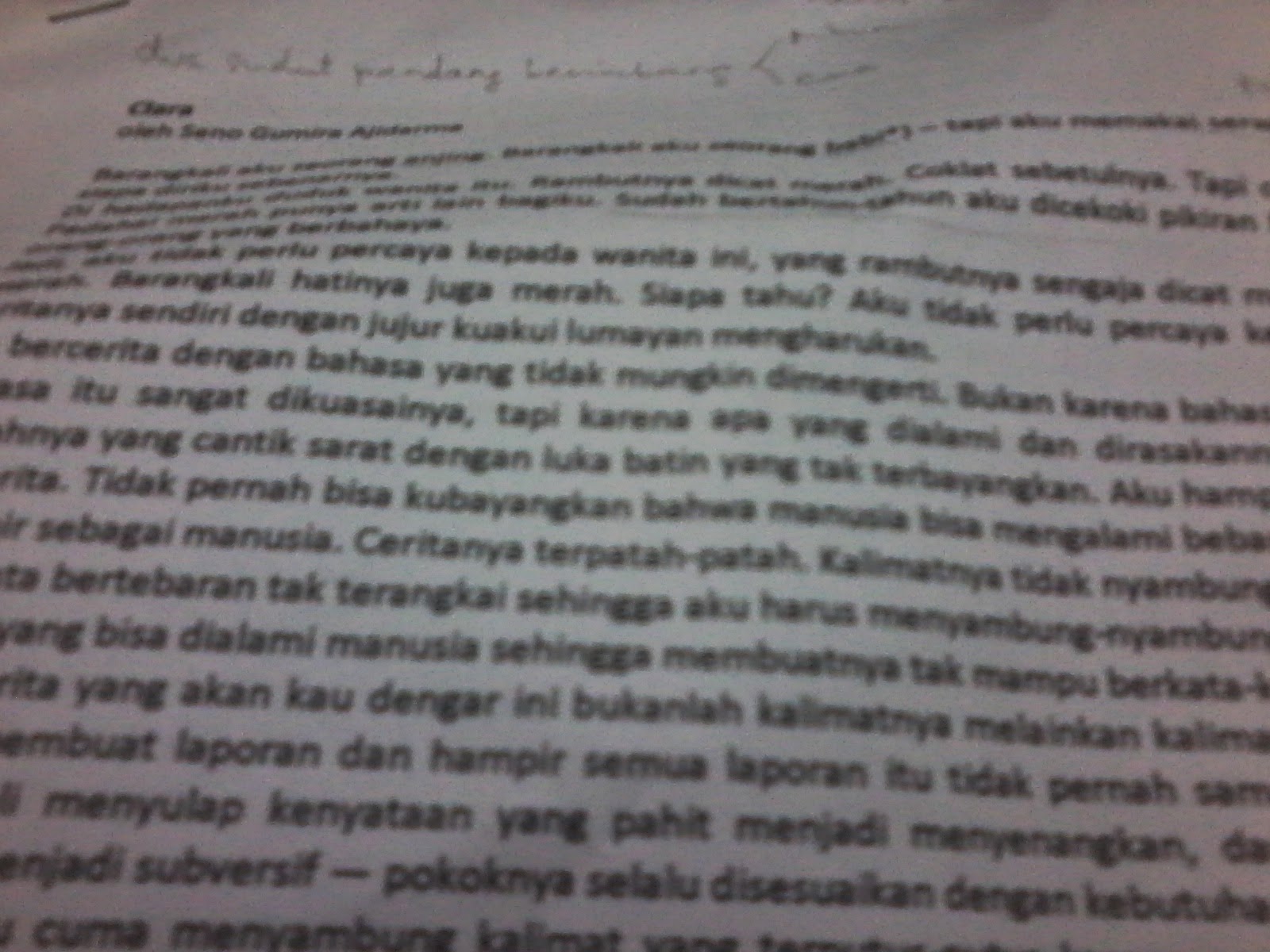Ide menarik kadang tercetus dari obrolan
pada waktu senggang. Begitulah antara
Kang Adew dan
Nurul hingga muncul ide
untuk menapaktilasi
panineungan
(:kenangan) H. Us Tiarsa R. dalam buku
Basa
Bandung Halimunan. Jadi membaca bukan sekadar membaca melainkan sembari
mengalami langsung apa yang disuguhkan dalam bacaan. Datangi tempat-tempat yang
dirujuk di dalam buku. Bandingkan apa yang tertulis di dalam buku dengan
kenyataan yang kita lihat. Metode ini hampir serupa dengan yang dilakukan oleh
Komunitas Aleut. Namun komunitas tersebut tidak secara spesifik menyebutnya
sebagai “pembacaan”—atau istilah yang lazim kami pakai: “tadarusan”. Buku
dipegang sebagai pendukung keterangan dari koordinator atau narasumber, dan
jumlahnya bisa lebih dari satu. Adapun Kang Adew mengacu pada hanya satu buku
yaitu
Basa Bandung Halimunan. Buku
ini merupakan kumpulan tulisan H. Us Tiarsa R. mengenai keadaan Bandung
sebagaimana diamatinya pada tahun ’50-’60-an. Tulisan-tulisan tersebut pendek
saja, sekitar dua-tiga halaman, dan sebelumnya dimuat di sebuah media berbahasa
sunda. Adapun “basa Bandung halimunan” sendiri berarti “sewaktu Bandung berkabut”.
Sekarang pun Bandung masih berkabut—oleh polusi.
Kang Adew ini pegiat di Asia-Africa
Reading Club (AARC), Museum Konperensi Asia Afrika, yang punya program tadarusan
buku tokoh-tokoh Asia-Afrika setiap Rabu, pukul 16.30 – 20.00 WIB. Saya pertama
kali mengikuti acara ini sewaktu buku yang ditadaruskan adalah
Di Bawah Bendera Revolusi karya bapak
proklamator kita, Soekarno. Setelah buku tersebut tamat, tadarusan dilanjutkan
dengan buku Nelson Mandela, dan kini, Mochammad Hatta. Saya bukan pengikut
setia AARC kendati setiap pulang dari acaranya saya merasa mendapat semacam
semangat untuk mulai berpikir besar, berpikir global. Biasanya tadarusan
dilakukan di salah satu ruangan di Museum. Mereka melakukan napak tilas juga,
sesekali. Nah, konsep itu pula yang hendak diterapkan pada
Basa Bandung Halimunan, namun kali ini napak tilas sudah pasti
dilakukan karena isi buku tersebut memang menyerupai panduan perjalanan (ke
masa lalu) dengan deskripsi tempat dan sebagainya—alih-alih pemikiran
sebagaimana dalam tadarusan rutin AARC—dan tentunya semangat yang diusung
berbeda yakni semangat untuk lebih mengenal kota yang kami tinggali sekalian
belajar bahasa sunda—karena dalam bahasa tersebut buku itu ditulis. Konsep “tadarusan”
berarti teks dalam buku itu dibacakan keras-keras oleh seseorang atau
bergantian, lalu yang mengerti bahasa sunda akan mengartikan kata-kata tertentu
sehingga yang tidak begitu mengerti bahasa tersebut (seperti saya) dapat
memahami apa yang diceritakan. Harapannya, pembacaan napak-tilas ini dapat
memantik teman-teman yang mengikutinya untuk menuangkan warna-warni kehidupan
kota, realitasnya, menjadi sebentuk karya—karya apapun—seperti yang dicontohkan
oleh
para penyair,
sastrawan…
 |
Potret iseng sewaktu Ukeba (pojok kiri)
tampil di IFI dalam rangka Record Shop
Festival (atau semacam itu), Sabtu, 19/4/14 |
|
Ide ini tadinya hendak mulai
dilaksanakan pada 19/4/14, di sekitar Jalan Wastukencana—sebagaimana yang
dirujuk dalam tulisan pertama buku tersebut. Namun karena pada waktu itu Kang
Adew ternyata ada jadwal manggung di Institut Français Indonesia
aka IFI bersama Komunitas Ukulele Bandung
alias Ukeba, maka alih-alih melakukan pembacaan sambil jalan-jalan, kami malah
menjadi
groupies-nya Kang Adew, eh,
Ukeba. Namun sebelum penampilan grupnya, Kang Adew menyempatkan diri untuk
memberikan pengantar dan, sesudahnya, melakukan pembacaan bersama tulisan yang tadinya hendak dinapaktilasi itu. Ganjil memang rasanya, mengulas
bacaan berbahasa sunda di teritorial Prancis....
Dua minggu kemudian pembacaan
napak-tilas benar-benar dilaksanakan sebagaimana diinginkan. Mereka mulai dari
tulisan berjudul “Setatsion”—Stasiun. Kumpul pada pukul 13, blusukan, sampai kira-kira pukul 16.
Mereka sempat mampir ke UNISBA untuk mencari jejak kuburan Belanda alias kerkop—sundana mah. Sayang pada waktu
itu saya tidak bisa ikut.
Dua minggu berikutnya, Sabtu, 18/5/14, akhirnya
kesempatan itu datang pada saya. Kami berkumpul di Stasiun Bandung sebelah
utara pada pukul 13 Waktu Indonesia Karet. Tulisan yang hendak dinapaktilasi
berjudul “Numpak Kapal”, bisa diartikan menjadi “Menaiki Pesawat” karena “Kapal”
yang dimaksud adalah “kapal terbang”—sebab keberadaan “kapal laut” di daerah
yang tidak punya pantai seperti Bandung itu tidak lazim. Kami pun mencari
tempat-tempat yang dirujuk dalam tulisan tersebut, di antaranya Jalan H. Iskat dan
susukan Ciguriang.
Kami menduga Jalan H. Iskat terletak di seberang
stasiun, namun karena ada banyak jalan di sana dan kami tidak pasti yang mana,
kami asal saja memasuki salah satunya, lalu menanyakan pada orang yang lewat di
mana lokasi itu persisnya. Seorang ibu-ibu berbaik hati menuntun kami menemukan
jalan tersebut, sekalian beliau sendiri menuju rumahnya yang terletak di jalan
lain. Kang Adew mengaku kami mencari jalan tersebut untuk menemui saudaranya.
Jalan H. Iskat kini telah menjadi
pemukiman. Ada satu hotel yang terselip di antara rumah-rumah. Kami duduk di
depan pagar salah satu rumah yang tampak asri. Pembacaan pun dimulai. Sembari
mengartikan teks tersebut, Kang Adew menambahkan situasi yang melatarinya.
Pada tahun 1946, masa agresi pertama
Belanda, warga Bandung memilih untuk membakar kotanya, tidak seperti warga
Surabaya yang melawan agar tidak dijajah kembali. Pemuda Bandung pun dikatai
pemuda peuyeum oleh pemuda Surabaya. Peuyeum kan lembek. Bagaimanapun, strategi itu dipilih karena warga Bandung kekurangan
senjata. Nah, kawasan stasiun alias Kebonkawung itu termasuk yang dibakar. Pada
tahun 1949, penulis Basa Bandung
Halimunan menengok kawasan tersebut dan mendapati bahwa Jalan H. Iskat yang
dulunya bernama Gang Litsonlan itu masih berupa kebun yang luas. Bangkai kapal
(ingat, yang terbang) dan mobil patihsolengkrah—berserakan,
tertutup oleh alimusa, lameta, eurih—semak belukar. Pada permukaan tubuh kendaraan tersebut
terdapat lubang-lubang bekas peluru. Agaknya kapal merupakan sisa perang, namun
mobil yang ditemukan umumnya mobil sedan seperti Fiat, Buick, dan sebagainya. Anak-anak
setempat menjadikannya mainan. Mereka mengaku-ngaku kendaraan-kendaraan itu
seolah milik mereka. Yang mobil diakui sebagai milik perorangan, sedangkan yang
kapal dipakai ramai-ramai. Ada yang berpura-pura menjadi pilot. Ada yang
berpura-pura menjatuhkan bom. Ada yang berpura-pura menembakkan senjata. Bermain
serdadu-serdaduan. Masing-masing menirukan bunyi entahkah pesawat, bom, atau
senjata, sampai tutup telinga segala seolah kebisingan itu sungguh-sungguh
terjadi. Boleh jadi imajinasi mereka memang tinggi. Bisa pula karena mereka mengalami
sendiri bagaimana huru-hara perang. Kadang mereka bertemu sinyo yang bisa
berbahasa sunda dan mengajak bermain, namun mereka malah malu-malu. Lagipula
orangtua mereka menakut-nakuti kalau Belanda itu jahat, suka membunuh, dan sebagainya.
Serakan bangkai tersebut kini jelaslah sudah dibersihkan, entah dibawa ke mana…
 |
Jalan H. Iskat sekarang, tampak dari sebelah utara.
Dulunya kebun penuh bangkai kendaraan. |
 |
Kalapa cina, salah satu tumbuhan yang
menaungi balong |
Nah, masih dalam kawasan tersebut
terdapat susukan Ciguriang. Kang Adew menanyakan tempat tersebut kepada warga
setempat yang lewat, mengaku sedang mengadakan penelitian. Dalam buku
disebutkan bahwa dahulu para warga
sok
ngajengjehe alias jongkok
sorrow
di sekitar situ, tahulah sedang apa… Atap bangunan yang diduga berada dalam
kompleks GOR Pajajaran sudah terlihat. Kami memasuki jalan kecil beberapa jauh
di belakangnya, dan menemukan tempat yang secara menakjubkan
kok masih ada di tengah perkotaan macam
Bandung ini: balong!—yang diteduhi oleh pepohonan rindang di sekelilingnya, dan
di seberangnya terdapat tanah kosong. Menurut buku, tempat semacam itu dihuni banyak
ular. Jadi, hati-hati kalau bermain di sana!
Omong-omong soal
ngajengjehe, kata ini hanya satu dari berbagai varian “jongkok”
dalam bahasa sunda. Istilah lain yang dikenalkan dalam obrolan adalah
cineten dan
cingogo, dan mungkin ada lagi. Sayang, masing-masing tidak
diperagakan dengan jelas. Selama ini saya hanya tahu
cingogo, dan posisi jongkok—bagaimanapun variasinya—biasanya diasosiasikan
dengan buang air. Selain “jongkok”, terdapat pula variasi untuk “jatuh”,
seperti
tikusruk,
tisoledad, dan sebagainya, yang dalam
bahasa Indonesia pun variasinya sebenarnya cukup banyak: “terjungkal”, “terjengkang”,
“tersungkur”, “terjerembap”, dan lain-lain. Sungguhpun begitu agaknya bahasa
daerah masih jauh lebih kaya, seperti dalam bahasa sunda. Variasi lain dalam
bahasa sunda yang saya ketahui adalah untuk kata “liur”, bisa disebut
dahdir,
jigong,
acay,
hokcay. Saya pernah punya
teman mengumpulkan kata-kata “jorok” dalam bahasa sunda, sebagaimana yang saya sudah
sebut tadi, ditambah dengan kata-kata lain seperti
leho (ingus),
cileuh
(belek), dan saya lupa apa lagi, dan mendengar kata-kata tersebut diucapkan saja
sudah membuatnya tertawa-tawa seperti kuntilanak karena terasa lucu di
telinganya.
 |
| Balong yang diduga sisa susukan Ciguriang |
 |
| Mencegat warga setempat untuk mendapatkan keterangan |
 |
| Ayam-ayam mengaso di sofa rongsok |
 |
| Memeragakan posisi ngajengheng |
Anyway, pembacaan dilanjutkan di tribune GOR Pajajaran.
Kebetulan tulisan berikutnya, yang berjudul “Mandor Atma”, secara khusus
bercerita mengenai tempat tersebut. Entahkah para pengunjung lainnya yang
membersamai kami pada hari yang mulai redup itu tahu kalau mereka tengah
menduduki bekas
kerkop alias
pekuburan… Biarpun begitu, pada masa lalu
kerkop telah menjadi ruang publik tempat warga menghabiskan waktu senggang. Anak-anak
bermain, mengambili pecahan marmer untuk dijadikan kelereng atau apa. Ada yang
piknik. Ada yang pacaran, mungkin seperti dalam lagu lawas yang dinyanyikan
oleh Rien Djamain, “Menanti di Bawah Pohon Kemboja”. Ada juga yang membaca, mungkin
patut dicoba oleh pencinta buku. Pada tahun ’60-an, pekuburan itu dijadikan
GOR. Sebagian penghuni dibawa pulang kampung oleh keturunannya, sebagian lagi
dipindahkan ke
Makam Pandu. Adapun Mandor Atma adalah nama kuncen penghuni
bedeng di pekuburan tersebut. Pekerjaannya mengusiri orang-orang jahil.
 |
Salah satu sisi GOR Pajajaran. Dulunya pekuburan.
Gedung di seberang adalah gedung KONI Jabar. |
Kini kami termasuk orang-orang yang
menghabiskan waktu senggang di pekuburan, walau bentuknya sudah berupa GOR. Mereka
yang memiliki banyak waktu senggang terkesan menganggur, dan sedihnya itu
menjadi stigma. Padahal, Kang Adew bilang, ide-ide besar ada kalanya lahir dari
sekumpulan orang yang gemar duduk santai di warung kopi alih-alih dalam situasi
formal. Nangkring produktif,
istilahnya mungkin begitu. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan
pembacaan napak-tilas ini, mudah-mudahan. Nah, siapa mau ikut dalam kesempatan
selanjutnya? Cung!