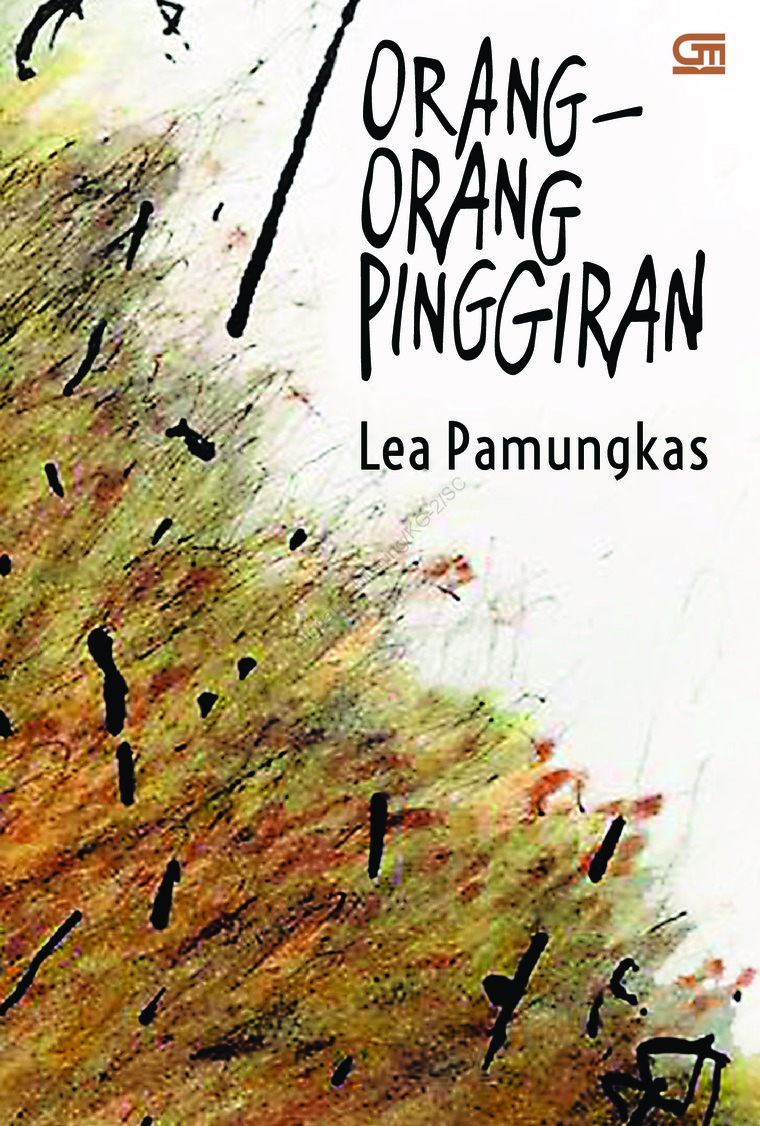Pada Sabtu, 30 November 2019, saya berkesempatan menghadiri acara peluncuran buku di Perpustakaan ITB. Saya datang sekitar pukul setengah dua, sementara menurut jadwal acara baru dimulai pukul dua. Setelah menandatangani daftar hadir, saya mencari tempat strategis untuk duduk dan membaca sembari menunggu. Sesekali saya celingukan memerhatikan yang sudah hadir atapun yang baru datang, mencari kalau-kalau ada yang saya kenal, sekalian menerka-nerka yang mana yang akan berbicara tentang apa.
Sementara itu, di depan, layar proyektor menampilkan ilustrasi dalam buku secara berganti-ganti. Gambar-gambarnya sangat khas anak-anak, beberapa tampaknya diwarnai dengan krayon.
 |
Grrr, maaf, kamera ponsel saya kurang asyik.
Kurang lebih beginilah gambaran samar-samar ilustrasinya. |
Pandangan saya lalu bertumbuk pada seorang mbak-mbak berbaju kuning. Dengan ramah ia menyalami saya. Saya mengira ia mengajak berkenalan, sehingga saya menyebutkan nama saya tapi saya tidak dapat mendengar namanya dengan jelas.
Menakjubkan, acara dimulai tepat pukul dua. Sementara MC mulai bercuap-cuap, para pembicara pun duduk di kursi-kursi yang telah disediakan di depan. Saya masih menduga-duga yang mana yang siapa.
Ternyata mbak-mbak berbaju kuning yang menyalami saya tadi adalah penulisnya.

Menakjubkan lagi, buku cerita anak ini rupanya diterbitkan oleh ITB Press.
Tunggu, tunggu, tunggu, bukannya ITB Press itu penerbit buku-buku kuliah?
Lebih menakjubkan lagi, penulis sampai mendatangi profesor ahli astronomi untuk riset bakal bukunya.
Karena profesor yang bersangkutan tidak dapat hadir, maka digantikan oleh putranya, Bapak Arif Arianto. Beliau dipersilakan untuk memberikan sambutan pertama. Rupanya beliau dan penulis sama-sama bekerja sebagai perekayasa di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Beliau juga memberikan gambaran (atau "resensi", kata beliau) mengenai isi buku. Misalnya saja, dalam buku ini ada sepuluh cerita dan salah satu di antaranya memuat rumus tentang bintang ....
What ....
Di samping itu, terdapat banyak pengetahuan lainnya tentang kearifan lokal, tata bintang, cara menyangrai kopi, dan lain sebagainya. Singkatnya, ini merupakan buku kumpulan cerita anak ilmiah.
Setidaknya, ada dua pesan dalam buku ini. Yang pertama, yaitu tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua, yaitu mengenai
soft skills--nilai-nilai kepribadian seperti cermat, jujur, dan integritas.
Bapak Edi Warsidi selaku editor ITB Press kemudian maju untuk memberikan sambutan kedua. Beliau menerangkan bahwa karya ini memang buku anak pertama yang diterbitkan ITB Press.
Sambutan berikutnya disampaikan oleh perwakilan dari Kumpulan Emak Blogger (KEB), yang sepertinya merupakan komunitas utama yang diundang dalam acara ini, di samping sebagai sponsor. Tampaknya sebagian besar peserta yang hadir merupakan anggota KEB.
(Lah, saya siapa?)
Kemudian tibalah giliran penulis untuk menceritakan tentang proses kreatifnya. Rupanya karya ini bukan buku anak-anak pertama beliau. Ada beberapa karangan lainnya yang telah diterbitkan, di antaranya oleh penerbit DAR! Mizan. Beberapa buku itu selalu berjudul
Misteri Hantu Sesuatu, hingga kali ini beliau mendapat ide untuk membuat yang lain. Cikal-bakalnya terinspirasi dari obrolan masa kecil dengan ayahnya tentang bintang kejora yang ternyata bukan bintang, melainkan Planet Venus. Beliau pun mencari alamat ahli astronomi,
Profesor Bambang Hidayat. Ketika datang ke rumahnya, rupanya Profesor Bambang tidak sendirian tapi disertai profesor-profesor lain .... Wow.
 |
Pemandangan dari bangku saya, bila saya berdiri.
Dari kiri saya ke kanan: Pak Arif, ilustrator, penulis, Pak Ali, dan Pak Edi. |
Penulis pun lalu membicarakan tentang ide ceritanya ini kepada ilustrator, Mbak Tanti Amelia. Mbak Tanti lalu mengusulkan untuk membuat kumpulan cerita tematik tentang alam semesta. Maka cerita dalam buku ini pun bukan hanya tentang astronomi, melainkan berkembang menjadi berbagai soal termasuk isu lingkungan hidup seperti cara menanam tumbuhan dan menyikapi sampah plastik. Pada akhirnya, buku ini terdiri dari 161 halaman dan 41 gambar. Proses pengembangan cerita sampai penerbitan memakan sepuluh bulan. Sementara itu, beliau intens dikirimi bahan dan buku terkait oleh para profesor.
Bapak Edi Warsidi lalu berbicara lagi, menerangkan tentang proses penyuntingan. Pertama-tama, dilakukan pembacaan dari awal sampai akhir. Baru setelah itu dilakukan penyuntingan bila ada yang perlu. Penyuntingan di sini lebih pada hal teknis seperti tata bahasa dan tanda baca. Adapun soal konten telah dilakukan oleh profesor.
Kemudian tiba giliran Bapak Ali Muakhir dari Forum Lingkar Pena (FLP) sebagai pengulas. Nah, di sini yang seru. Beliau tidak sekadar membahas tentang buku ini, tapi juga menyertakan "aturan-aturan" dalam menulis cerita anak.
Pertama-tama, alih-alih konten, kita semestinya memikirkan tentang sasaran pembaca. Ada semacam kategorisasi dalam dunia bacaan anak. Misalnya saja, ada "kelas rendah" untuk anak-anak kelas 1-3 SD dan "kelas tinggi" untuk kelas 4-6 SD. Cara menuliskan cerita untuk kelas rendah berbeda dengan untuk kelas tinggi.
Adapun buku
Aku dan Alam Semesta ini, menurut Pak Ali, cocoknya bagi pembaca kelas akhir atau usia praremaja.
Kedua, di samping usia, ada juga soal tempat. Misal, bacaan untuk anak Bandung berbeda dengan untuk anak Papua--pada rentang usia yang sama. Pak Ali memberikan contoh dari kunjungannya ke Kalimantan, di sana
picture book yang sedianya untuk anak TK malah dikonsumsi oleh anak kelas 3 SD.
Kemudian beliau memaparkan tentang kriteria fiksi anak yang baik, kurang lebih sebagai berikut.
1) Inspiratif
2) Cara penyampaian sesuai dengan sasaran pembaca
3) Tidak mengandung unsur negatif
Unsur negatif ini misalnya soal
body shaming, menyebutkan ciri fisik tertentu seperti "gendut", "pincang", dan sebagainya.
4) Fokus pada satu masalah atau gagasan saja
Adapun dalam buku ini ada banyak sekali hal yang ingin disampaikan.
5) Kalimat mudah dipahami, misalnya tiap kalimat dapat dibaca dalam satu tarikan napas
Dalam buku ini ada penjelasan-penjelasan teknis yang cukup berat.
6) Tokoh harus anak-anak, biarpun ada juga cerita anak-anak bertokoh orang dewasa yang bagus
Pak Ali memberikan beberapa contoh cerita anak lainnya yang bagus dan kreatif dalam menyampaikan wawasan sains. Misalkan saja, ada suatu cerita berisi pelajaran perkalian yang disampaikan melalui tokoh vampir. Ada juga cerita yang menjelaskan tentang gelombang ultrasonik melalui adegan pesta para kelelawar.
Hmmm, saya jadi ingat bahwa saya sendiri pernah mencoba untuk menyampaikan pengetahuan tertentu dalam kemasan cerita anak, walaupun saya tidak tahu apakah sudah berhasil atau belum.
Cerita yang satu saya ikutkan dalam lomba, tapi tidak menang.
Cerita yang lainnya saya buat untuk lomba yang lainnya lagi, dan menang, tapi lingkupnya kecil-kecilan saja. Pada waktu itu memang saya belum tahu aturan-aturan dalam membuat cerita anak
, (sekarang juga belum sih).
Kata Pak Ali, referensi dalam membuat cerita anak di Indonesia hanya
Bobo. Eh, lagi-lagi saya ingat pada percobaan saya untuk meng
kliping cerpen dan dongeng Bobo di Wattpad--mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi mereka yang ingin belajar menulis cerita anak.
Terakhir, Mbak Tanti Amelia selaku ilustrator diminta menceritakan tentang proses kreatifnya. Untuk buku ini, beliau telah membuat banyak gambar, walaupun tidak sampai seratus. Dari 41 gambar yang dipilih, ada yang sebenarnya hanya sketsa tapi mengandung ekspresi yang pas. Pengalaman yang sulit yaitu untuk tiga cerita terakhir; tulisannya belum ada tapi beliau sudah diminta untuk menggambar. Malah ada gambarnya yang di"koreksi" (: dicoret-coret) oleh profesor.
Sesi tanya jawab pun dibuka sampai dua kali. Pada sesi pertama ada tiga penanya, dan pada sesi kedua ada empat. Pertanyaan-pertanyaan ini memancing penulis, ilustrator, dan editor untuk membeberkan lebih lanjut mengenai proses
behind-the-scene mereka.
Bagi penulis, dalam penulisan buku ini, beliau sesungguhnya sempat agak BT karena ada banyak koreksi. Adapun inspirasinya dalam menulis yaitu buku-buku bacaannya dulu, seperti karya Nh. Dini, serial
Lima Sekawan, Nicholas Sparks, dan Danielle Steel. Beliau menganjurkan agar bergabung dengan komunitas-komunitas, untuk menjaga keaktifan dan ketertiban berkreasi.
Setelah saya melihat-lihat
blog penulis, ternyata beliau memang perempuan luar biasa. Di samping perekayasa BPPT dan penulis 17 buku antologi serta 8 buku solo, beliau juga seorang istri dan ibu tiga anak. Hobi beliau pun bukan hanya menulis, melainkan juga menggambar, jalan-jalan, bahkan
bermusik. Malah beliau bisa bertemu dengan ilustratornya karena sama-sama memenangkan lomba
doodle Google.
Ilustrator menceritakan tentang kesenangannya menggambar semasa sekolah dan kuliah yang sempat terhenti. Aktivitasnya menggambar dimulai lagi saat beliau mencela kalender produksi kantornya, sehingga beliau ditantang oleh atasannya untuk membuat yang lebih bagus. Beliau tidak suka menggunakan cara digital dalam menggambar, yang justru sesuai dengan proyek buku yang mengusung kearifan lokal ini. Ilustrator dan penulis berencana untuk membuat buku-buku lainnya.
Menurut Mbak Tanti, tidak ada gambar yang jelek atau istilahnya "
there's no mistake in art". Beliau menyarankan untuk memulai dari
doodle dulu atau
vignette, semacam coret-coret bebas.
Adapun editor menjelaskan tentang diterbitkannya buku ini dalam dua versi, yaitu versi berwarna dan versi hitam putih. Sederhananya, kata beliau, versi hitam putih itu edisi ekonomis sedangkan versi berwarna itu edisi luks. Dalam buku ini, penekanannya lebih pada cerita atau renungan sehingga warna pada ilustrasi tidak begitu penting. Beliau juga menerangkan bahwa apa yang bisa dijelaskan lewat ilustrasi sebaiknya tidak perlu dideskripsikan lagi melalui tulisan. Misalkan saja, bagian-bagian tumbuhan kelapa dapat ditunjukkan lewat ilustrasi, sehingga dalam tulisan dipaparkan saja mengenai fungsi-fungsinya.
Selain itu, misi ITB Press sebenarnya memang menerbitkan keperluan kuliah dalam lingkup fakultas-fakultas yang ada di ITB. Tapi toh buku fiksi anak karya de Laras ini memang mencakup pokok-pokok yang diajarkan di ITB, yaitu sains, teknologi, dan seni. Penerbitan buku semacam ini bisa dibilang merupakan program pengayaan yang mudah-mudahan bisa diakomodasi mulai 2020.
Acara pun ditutup tapi belum selesai. Ada banyak suguhan lainnya, seperti pesan sponsor, bagi-bagi hadiah untuk peserta, pemberian kenang-kenangan kepada pembicara, foto bersama, pembagian
goodie bag, serta
coffee break.
 |
| Hampir semuanya yang hadir berfoto bersama. |
Acara ini memang didukung oleh banyak sponsor. Selain komunitas KEB, ada juga Faber Castell, Dunkin Donuts, MQTV, Harris (hotel), Tiara (
online book store), Musafir (hotel), dan RedDoorz. Karena itu, ada banyak suguhan untuk para peserta. Hanya beberapa peserta yang beruntung yang mendapatkan buku edisi berwarna dari penulis serta voucer menginap di Harris dan Musafir. Tapi semua peserta mendapatkan voucer dari RedDoorz,
goodie bag yang isinya
incredibly amazing (yang jelas ada produk-produk Faber Castell, ITB Press, serta beberapa lagi yang spesial dari penulis), kopi/teh/air putih, dan aneka
snack yang di antaranya donat Dunkin Donuts.
Peserta juga dapat langsung membeli buku penulis di tempat; yang berwarna seharga Rp 150.000 adapun yang hitam-putih Rp 50.000. Bagi yang tidak sempat, buku dapat dipesan melalui
Tiara.
Berikut liputan dari MQTV.